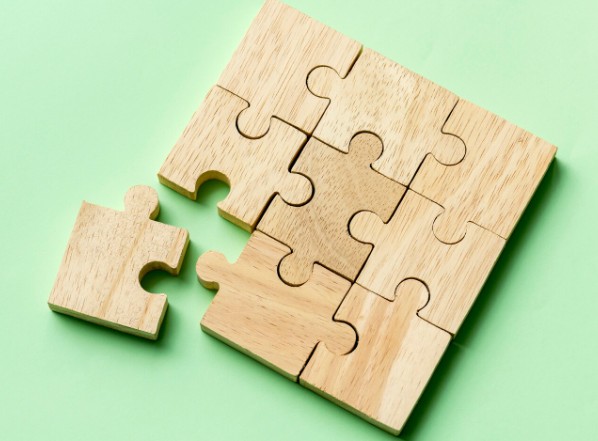Pendahuluan
Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan. Ia adalah aktor utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, hingga pembayaran. Maka dari itu, keberlangsungan dan konsistensi peran PPK sangat penting untuk menjamin bahwa setiap proyek pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, rencana kerja, dan anggaran yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, sering kali kita temui PPK diganti di tengah proses, baik karena mutasi, promosi, pergantian kepemimpinan, atau alasan administratif lainnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan. Artikel ini akan membedah secara komprehensif dampak dari seringnya pergantian PPK terhadap berbagai aspek dalam proyek pengadaan, dari tahap awal hingga akhir, serta menyodorkan strategi mitigasi agar risiko dapat diminimalisasi.
1. Memahami Peran Vital PPK dalam Sistem Pengadaan
PPK bukan sekadar pejabat administratif yang menandatangani dokumen. Ia adalah pemegang otoritas atas pelaksanaan kontrak. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK ditugaskan untuk menetapkan rencana pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dokumen pemilihan, menetapkan pemenang (dalam beberapa kondisi), menandatangani kontrak, hingga mengawasi dan melakukan pembayaran. Dengan tanggung jawab sebesar ini, pergantian PPK sama dengan mengganti otak sentral yang mengelola informasi, kebijakan, dan arah teknis sebuah proyek.
Setiap keputusan yang diambil PPK berimplikasi langsung terhadap waktu, biaya, dan mutu (time, cost, quality) proyek. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan karena minimnya pemahaman atau informasi dari PPK baru, maka konsekuensinya bisa mencakup keterlambatan pekerjaan, ketidaktepatan pembayaran, hingga potensi sengketa hukum. Maka dari itu, stabilitas posisi PPK menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pengadaan, terutama untuk proyek strategis atau bernilai besar.
2. Penyebab Umum Pergantian PPK dan Tantangannya
Pergantian PPK tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi fenomena ini. Mutasi jabatan secara berkala merupakan salah satu kebijakan manajemen ASN untuk penyegaran organisasi dan pengembangan kompetensi pegawai. Selain itu, rotasi sering kali dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan atau konsentrasi kekuasaan pada satu individu. Tak jarang pula pergantian dilakukan karena faktor kedisiplinan, ketidakmampuan teknis, atau tekanan dari pihak eksternal seperti pimpinan instansi atau auditor.
Namun, permasalahan muncul ketika pergantian tersebut tidak diiringi dengan proses alih tugas yang terstruktur. PPK baru sering kali harus “meraba-raba” situasi proyek yang sudah berjalan separuh. Ia tidak memiliki cukup waktu untuk memahami kronologi kegiatan, riwayat perubahan spesifikasi, hingga dinamika komunikasi dengan penyedia jasa. Ketika tidak ada dokumentasi atau sistem informasi proyek yang terdokumentasi dengan baik, maka kualitas pengambilan keputusan akan sangat terpengaruh. PPK baru kerap kali membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan pendahulunya, menyebabkan kebingungan di antara tim pelaksana proyek dan penyedia jasa.
3. Dampak Langsung pada Perencanaan Proyek
Salah satu fase paling krusial dalam pengadaan adalah perencanaan. Di sinilah rencana pengadaan dirancang, spesifikasi teknis ditetapkan, metode pemilihan penyedia dipilih, dan anggaran dialokasikan. PPK berperan aktif dalam penyusunan semua dokumen perencanaan tersebut. Bila PPK diganti sebelum proses pengadaan dimulai atau saat dokumen sedang dalam proses validasi, maka PPK baru berpeluang untuk melakukan revisi terhadap dokumen yang telah disusun.
Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, terjadi keterlambatan dalam proses karena PPK baru harus mempelajari dari awal dokumen yang ada. Kedua, bisa terjadi perbedaan persepsi atau kebijakan. Misalnya, PPK lama menyusun spesifikasi dengan pendekatan output-based, sedangkan PPK baru lebih konservatif dan memilih pendekatan input-based. Ini memicu revisi besar yang membuat waktu penyusunan dokumen menjadi molor. Ketiga, jika rencana pengadaan harus direvisi karena pergantian PPK, maka semua tahapan yang sudah berjalan-termasuk konsultasi dengan PA/KPA atau ULP-bisa tertunda, menciptakan efek domino terhadap proses tender yang sudah dirancang.
4. Dampak pada Pelaksanaan, Pengawasan, dan Progres Proyek
Pada tahap pelaksanaan kontrak, PPK adalah ujung tombak pengawasan. Ia memastikan bahwa setiap progres fisik dan keuangan berjalan sesuai rencana. Ketika PPK diganti di tengah pelaksanaan proyek, pengetahuan yang bersifat tacit knowledge (yang tidak tertulis) akan hilang. Misalnya, PPK sebelumnya sudah melakukan negosiasi informal dengan penyedia tentang percepatan progres, atau telah mengidentifikasi potensi keterlambatan akibat faktor cuaca dan telah menyusun strategi mitigasi. Semua informasi ini bisa tidak tersampaikan kepada PPK baru, sehingga keputusan yang diambil selanjutnya bisa tidak selaras atau bahkan bertentangan.
Lebih jauh, dalam kondisi proyek yang memiliki banyak pekerjaan tambah/kurang atau variasi pekerjaan, ketidakhadiran PPK lama menyebabkan penyesuaian kontrak menjadi terhambat. Penyedia jasa menjadi kebingungan kepada siapa harus menyampaikan addendum, siapa yang berwenang mengevaluasi volume pekerjaan tambahan, atau siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi di lapangan. Semua ini memicu potensi sengketa kontrak, keterlambatan pembayaran, dan penurunan kualitas pekerjaan karena penyedia tidak lagi memiliki kejelasan dalam eskalasi komunikasi.
5. Hubungan Komunikasi dan Kepercayaan dengan Penyedia Terpengaruh
Salah satu aspek yang kerap diabaikan dalam proses pengadaan adalah faktor relasi antar manusia. Hubungan antara PPK dan penyedia jasa yang terjalin dengan baik akan meningkatkan kepercayaan, keterbukaan informasi, serta efektivitas komunikasi. Ketika PPK sering diganti, hubungan emosional dan profesional yang sudah terbentuk menjadi terputus. Penyedia jasa merasa harus memulai dari awal lagi untuk membangun kepercayaan, yang tentu saja membutuhkan waktu dan energi.
Tidak jarang, penyedia jasa merasa ragu atau bahkan frustasi ketika setiap PPK memiliki gaya komunikasi dan pendekatan manajerial yang berbeda. Ada PPK yang responsif dan akomodatif, namun ada pula yang birokratis dan lambat dalam mengambil keputusan. Ketidakpastian ini mempengaruhi kinerja penyedia, terutama dalam menyikapi perubahan kondisi lapangan yang membutuhkan keputusan cepat. Akibatnya, progres proyek bisa melambat, dan penyedia lebih memilih untuk “main aman” daripada melakukan inisiatif yang produktif namun berisiko.
6. Risiko Hukum dan Administratif Semakin Tinggi
Proses pengadaan diawasi ketat oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPK sebagai pejabat yang menandatangani kontrak dan dokumen keuangan memiliki tanggung jawab hukum yang besar. Ketika terjadi pergantian PPK, maka tanggung jawab hukum dan administratif terhadap proyek yang sudah berjalan bisa menjadi kabur. Misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab bila ada pembayaran ganda? Apakah PPK baru berwenang menandatangani addendum atas kontrak yang dia tidak rancang? Atau bagaimana jika PPK baru menolak klaim penyedia yang sudah disepakati secara lisan oleh PPK sebelumnya?
Situasi ini berisiko menimbulkan dualisme tanggung jawab dan membuka ruang interpretasi hukum yang berbahaya. Jika tidak segera ditangani secara prosedural, hal ini bisa menimbulkan temuan pemeriksaan atau bahkan gugatan hukum dari penyedia yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, keberlanjutan dan kejelasan dalam struktur PPK menjadi penting untuk menghindari potensi pelanggaran administrasi, kerugian negara, hingga jerat pidana.
7. Strategi Mitigasi: Menyikapi Pergantian PPK dengan Sistematis
Agar dampak dari pergantian PPK bisa diminimalisasi, perlu ada pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur.
Pertama, setiap PPK wajib membuat dokumentasi kegiatan secara rinci dan berkala, mencakup status kontrak, catatan rapat, rencana kerja, progres fisik, serta risiko-risiko yang teridentifikasi.
Kedua, saat terjadi pergantian, harus dilakukan proses serah terima jabatan (STJ) yang bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga mencakup pemaparan substansi proyek, penyerahan semua dokumen, serta sesi diskusi mendalam mengenai kondisi terakhir proyek.
Ketiga, instansi pemerintah perlu membentuk project continuity team atau tim keberlanjutan proyek yang terdiri dari pejabat teknis, keuangan, dan pengawasan. Tim ini memastikan bahwa informasi proyek tidak hanya bergantung pada satu individu (PPK), tetapi terdokumentasi secara kolektif dan bisa diakses siapa pun yang terlibat. Keempat, pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga pusat harus mulai mengadopsi sistem manajemen proyek digital yang menyimpan semua informasi dalam platform daring agar pergantian PPK tidak lagi menjadi masalah besar karena semua data bisa ditelusuri secara cepat dan akurat.
Kesimpulan
Seringnya pergantian PPK adalah fenomena yang nyata dalam sistem birokrasi Indonesia, namun dampaknya terhadap proyek pengadaan sangat signifikan. Mulai dari keterlambatan, kesalahan administratif, kesenjangan komunikasi, penurunan kepercayaan penyedia, hingga risiko hukum, semua bisa terjadi bila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi untuk membangun sistem manajemen pengadaan yang tangguh terhadap perubahan personel. Dokumentasi yang baik, mekanisme suksesi yang terstruktur, dan digitalisasi informasi proyek menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran pengadaan meski terjadi perubahan aktor. Karena pada akhirnya, keberhasilan proyek bukan hanya tergantung pada individu, tetapi pada sistem yang mampu menopang setiap perubahan dengan konsisten dan profesional.